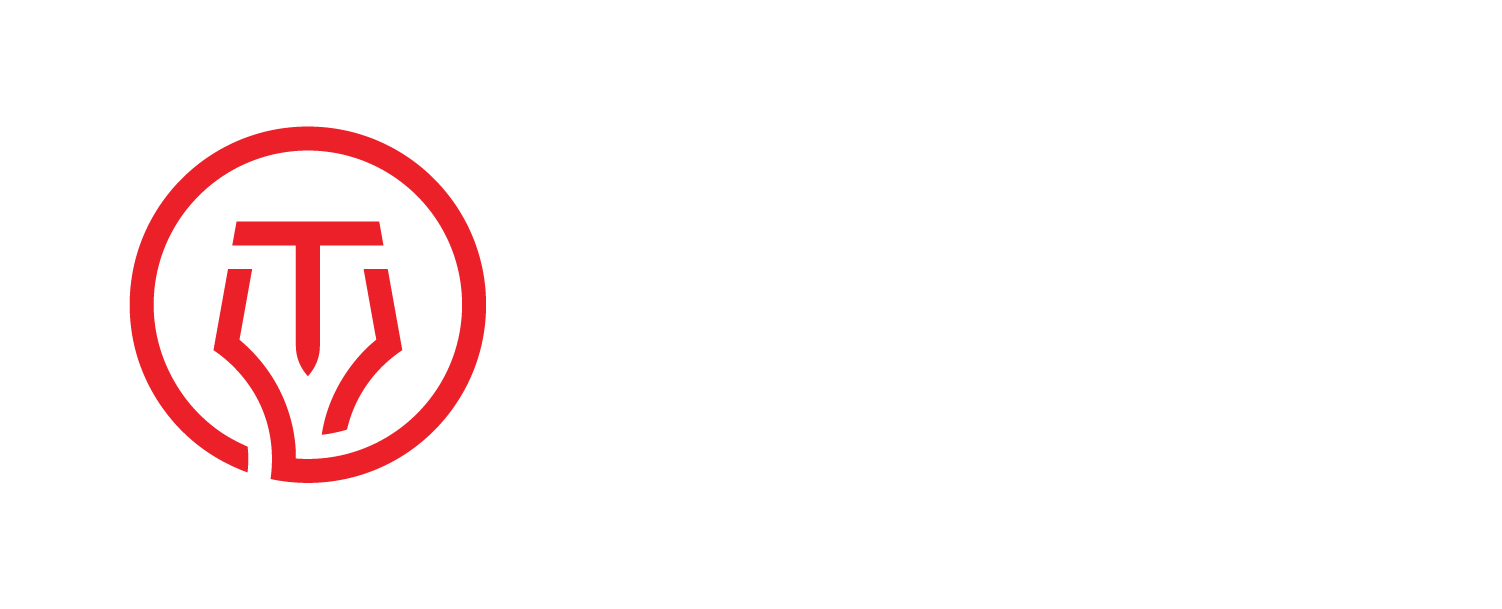Kolom
Monday, 10 September 2018 05:22 WIB
Kota-kota yang Merebut Kembali Jalan
Author pwtsetiadi
Oleh Purwanto Setiadi
Sebuah video yang belum lama beredar, berasal dari unggahan akun media sosial World Economic Forum, memperlihatkan sekuens gambar tentang bagaimana sebagian kawasan di sejumlah kota di Eropa telah dibebaskan dari kendaraan bermotor. Kecuali di Ljubljana, Slovenia, yang masih membolehkan taksi elektrik gratis untuk mengangkut orang tua, penyandang disabilitas, dan ibu yang membawa anak kecil, pusat keramaian di kota-kota itu didedikasikan sepenuhnya untuk pejalan kaki dan pesepeda. Pusat kota, tanpa mobil? Benarkah?
Gerakan membatasi mobil, di banyak kota bahkan dilakukan sampai ke tingkat yang mencengangkan itu, sesungguhnya perlahan-lahan telah menjadi semacam tren. Pada Maret lalu, misalnya, Los Angeles memutuskan tak akan menambah jalur di satu jalan bebas hambatan. Boleh dibilang, langkah kota terpadat kedua di Amerika Serikat ini di luar ekspektasi siapa pun, mengingat anggapan yang berlaku di sana adalah semakin banyak jalur berarti semakin sedikitlah kemacetan. Sebelumnya di Jerman, tempat teknologi diesel ditemukan, pengadilan tinggi telah memutuskan mobil berbahan bakar solar boleh dilarang masuk ke pusat-pusat kota demi mewujudkan udara yang bersih.
Kota-kota itu, negara-negara itu, terpisah satu dengan yang lain, dan bahkan terpaut jarak ribuan kilometer bila menyangkut California dan Jerman, tapi satu hal pasti: para pemimpinnya, dengan dukungan warganya, menyadari kenyataan bahwa kota tak bisa lagi dibiarkan semakin dijejali kendaraan bermotor, khususnya mobil. Bisa dilihat betapa di sana sudah timbul tekad untuk bertindak, yaitu mewujudkan jalan dan sisten transportasi yang berguna bagi setiap orang.
Kota-kota itu boleh dibilang telah belajar dari pengalaman bahwa pertumbuhan pesat jumlah mobil, juga semakin banyaknya mobil yang berkeliaran di jalan, yang digunakan sebagai sarana angkutan pribadi, telah memunculkan sekurang-kurangnya tiga masalah. Mula-mula yang timbul adalah setiap mobil menjadi rintangan, kalau bukan rival, mobil yang lain. Seorang pemilik mobil akan dengan mudah merasa jengkel terhadap mobil yang tak bergerak persis di depannya (bayangkan suasana hati yang sebetulnya berkecamuk di tengah-tengah situasi “parkir massal” di jalan). Semakin berjubel mobil di jalanan, bertambah lama pula waktu perjalanan dan kian parah polusi yang diakibatkannya.
Masalah kedua adalah, jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat, setelah sampai titik tertentu, membuat kota semakin tak menarik bagi pejalan kaki, pesepeda, dan orang yang bepergian dengan angkutan umum. Kendaraan bermotor juga mengenyahkan kumpulan anak-anak yang bermain dengan gembira di tempat terbuka, orang-orang yang duduk di bangku taman atau di kaki lima, bercengkerama dan mungkin membaca buku pada sore hari. Kita, dengan kata lain, menyerahkan ruang publik, percakapan antartetangga, dan pada akhirnya mobilitas pribadi demi tambahan kendaraan bermotor baru.
Yang tak kalah gentingnya adalah masalah yang tampak ganjil ini: pembangunan jalan baru tak benar-benar bisa menekan kemacetan; lebih sering justru memperburuk kemacetan yang ada. Para ahli sebetulnya telah lama menyadarinya, yakni bahwa segera setelah jalan raya baru rampung dibangun, atau jalur baru ditambahkan di jalan bebas hambatan, mobil akan bermunculan untuk mengisi kapasitas baru yang tersedia. Ujung-ujungnya, ya, terjadilah kemacetan lagi. Tapi, seperti luas diketahui, jalan keluar yang ditempuh tetap masih berupa pembangunan jalan atau jalur baru.
Semakin banyak kota yang memutuskan mengambil alih kontrol atas jalan di wilayahnya, dan menempatkan orang serta moda transportasi non-kendaraan bermotor pada tataran yang sama dengan kendaraan bermotor, tentu saja kabar yang membesarkan hati–kecuali, barangkali, bagi pabrik kendaraan bermotor dan agen penjualnya. Cara kota-kota itu melakukannya bisa berbeda satu dengan yang lain. London, misalnya, menerapkan pungutan kemacetan sejak 2003–belakangan, pada 2017, langkah ini disusul denda untuk kendaraan yang tak memenuhi standar emisi tertentu. Pungutan ini, mau tak mau, mengempesi minat pengendara untuk memasuki kawasan pusat kota. Oleh pemerintah kota, uang yang terkumpul digunakan untuk memperbaiki angkutan umum dan menambah jalur sepeda. Apa yang dilakukan London ini belakangan menjadi bahan kajian para pengambil kebijakan di beberapa kota di California.
Di Cina pembatasan malah diberlakukan dalam hal kepemilikan mobil. Di beberapa kota di sana orang boleh saja punya keinginan membeli mobil. Tapi mewujudkannya tak mudah. Di Shanghai orang mesti membeli pelat nomor melalui lelang, yang harganya terus melambung hingga setara harga mobil baru. Di Beijing ada proses lotere untuk mendapatkannya. Kita bisa menilainya sebagai kebijakan yang ekstrem. Tapi di Cina, yang pada 2010 sempat menanggung kemacetan sepanjang 100 kilometer dan perlu 11 hari untuk mengurainya, ini tindakan yang masuk akal.
Dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan kota-kota tersebut, kebijakan mengenai kawasan ganjil-genap yang diberlakukan Jakarta belum ada apa-apanya. Kebijakan yang cakupan wilayahnya diperluas menjelang pelaksanaan Asian Games itu memang disebut-sebut cukup berhasil melonggarkan jalan-jalan di pusat kota–dengan kata lain kemacetan berkurang. Tapi tanpa melanjutkannya (untuk sementara masih diperpanjang hingga pertengahan Oktober; di beberapa kawasan sudah tak berlaku) kebijakan ini bakal menyandang label sebagai langkah tambal sulam belaka, seperti kebijakan kawasan three-in-one yang dijalankan sebelumnya.
Supaya label itu bisa dihindarkan, tindakan yang melampaui “bisnis-seperti-biasa” sangat diperlukan. Bagaimanapun, harus ditegaskan bahwa saat inilah Jakarta, pemimpinnya, punya kesempatan untuk memutuskan di antara dua pilihan: yang rasional (dan menjadi satu di antara kota-kota yang telah tercerahkan; menimbang semua aspek yang membuat kota lebih sehat, nyaman, dan produktif, yang manusiawi) dengan membatasi secara permanen kendaraan bermotor, atau menutup mata terhadap kenyataan dengan terus melayani kelompok tertentu di dalam masyarakat dan terutama mereka yang diuntungkan oleh kian besarnya jumlah kendaraan bermotor yang terjual.
Yang membedakan pemimpin yang memilih di antara dua tindakan itu hanyalah yang pintar dan, ya, yang sebaliknya.
Penulis adalah wartawan, penyunting buku Jurnalistik Dasar: Resep dari Dapur Tempo, pernah menjadi Redaktur Pelaksana Tempo. Ia juga menulis tentang musik, kopi, dan sepeda di akun Facebook-nya.
Baca juga : Badan Siber dan Sandi Negara Akan Gandeng BIN, TNI, Polri